Jangan Lestarikan Bodobudur Jadi Monumen Komunikasi Penindasan Rakyat Kecil..!

Mendengar pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menaikkan tarif naik ke puncak Borobudur menjadi Rp 750 ribu bagi wisatawan lokal per orang, jelas membuat kaget. Sekaligus tercenung.
Entah mengapa ingatan ini tiba-tiba melayang bada buku bertajuk 'Kekalahan Manusia Petani: dimensi manusia dalam pembangunan pertanian, yang ditulis Greg Soetomo (publik mengenalnya sebagai Romo Tomo, Rohaniawan sekaligus aktivis pemberdayaanan para petani pedesaan). Buku ini dirilis oleh penerbit Kanisius, Yogyakarta. pada 1997. Buku ini saya baca sudah lama sekali dan selalu bergelayut dalam ingatan sejak saya baca diujung masa kuliah, yakni menjelang datangnya masa reformasi itu.
Di sana ada tulisan yang menyentak. Romo Tomo menulis bila setiap ada bangunan atau monumen besar (adiluhung) di dunia, pasti di sana terjejak kisah penderitaan rakyat. Tak peduli itu Piramid di Mesir, Taj Mahal di Agra India, Tembok Besar di Cina, Angkor Wat di Kamboja, Mausoleum di Roma, atau yang lainnya. Semua sama. Nasib dan kisah penderitaan rakyat kecil, misalnya para tukang, para pengepras batu, para penyedia makanan bagi tenaga kerja dan berbagai jenis pekerjaan pendukung dari proses lahirnya bangunan 'adilihung' itu, sama sekali tak tercatat. Bahkan diabaikan sejarah. Yang ada hanya kisah dan nama-nama sang penguasa, para Firaun, sultan, raja, hingga kaisar.
Di sana tidak ada kisah bagaimana cara bangunan itu dibuat oleh para pekerja yang jelas dari kalangan orang biasa dan tak punya. Apakah mereka dibayar ataukah hanya semacam kerja paksa mengingat kala itu zaman berada dalam era otoriterian. Tembok China misalnya bagaimana dibangun oleh para pekerja yang merupakan budak. Begitu juga Piramid. Ceceran darah, air mata, nyawa, hingga luka yang dialami para jelata pekerja tak ada kisah satu huruf pun yang menulisnya. Yang muncul dan dicatat zaman hanya glorifikasi kekuasaan. Padahal sejatinya bukan merekalah yang membangun dan mewujudkan bangunan tersebut.
Alhasil, bangunan yang adiluhung itu sebarnya tak ubahnya obyek komunikasi pecitraan dari sebuah dinasti atau sosok penguasa. Memakai bahasa lain hanya proyek 'Mercusar'. Rakyat dianggap layaknya hanya batu-batu tempelan di dasar alas candi yang letaknya berada di bagian bawah dan hanya pantas diinjak. Sedangkan di puncaknya adalah nama sang penguasa yang itu dilestarikan dan ditembangkan dari zaman ke zaman, dari kurun ke kurun.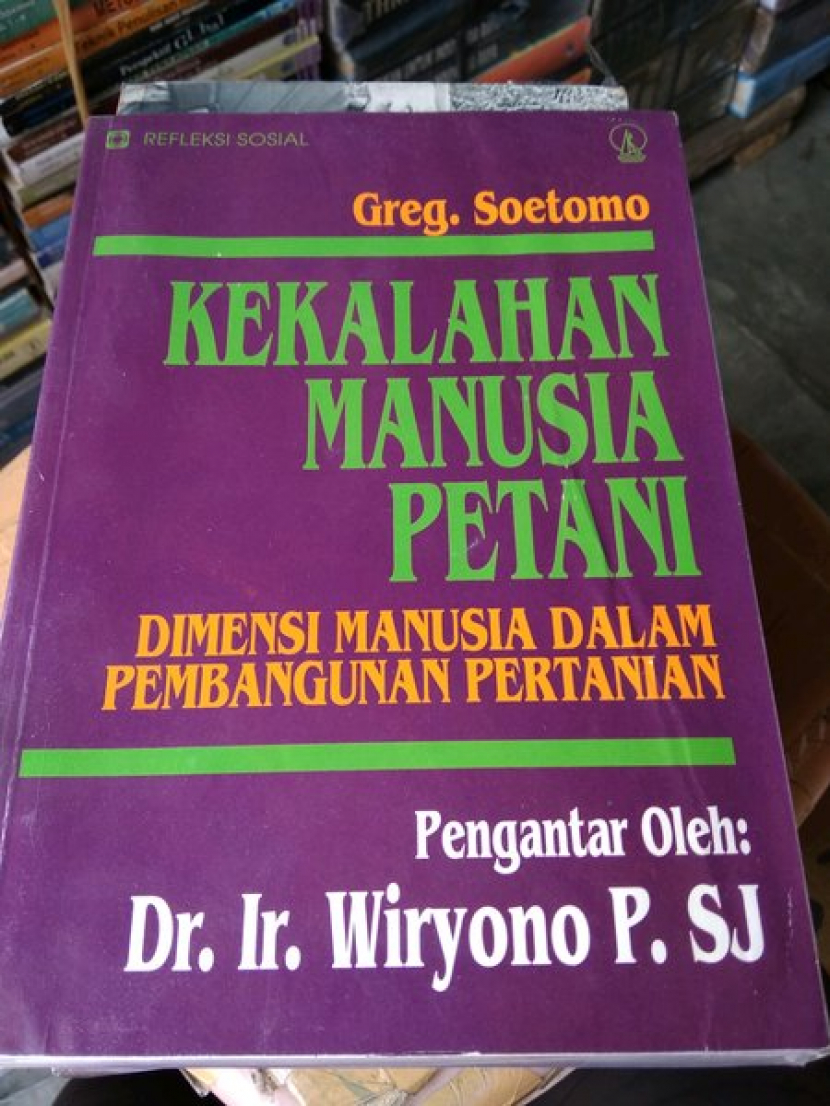
Jadi bila kini ada keinginan untuk membuat tarif selangit bila ada orang yang ingin naik ke puncak candi itu menjadi absurd. Pembangunan utamanya, yakni rakyat biasa yang lemah dan dahulu moyangnya membuat candi itu hanya gigit jari. Belum lagi ancaman menurunnya penghasilan mereka yang hidup di sekitar candi yang terimbas akibat merosotnya jumlah pengunjung atau turis yang datang. Sebab, nanti pasti hanya mereka yang kaya saja yang bisa menikmati puncak Borobudur. Rakyat kebanyakan hanya menjadi penonton pameran kesenjangan itu. Anak-anak bangsa ini pun ogah datang ke Borobudur karena diubah tangan kekuasaan menjadi monumen adiluhung yang hanya dinikmati orang 'elit' belaka.
Kalau sekedar alasannya menjaga situs agar lestari dan harus membatasi pengunjung naik ke atas, bukan caranya dilakukan dengan menaikkan harga selangit bila ingin ke puncak candi itu. Cukup atur waktu kunjungan. Dan, kini akan semakin mudah karena bisa diatasi dengan cara mengeluarkan tiket secara terbatas dan terjadwall melalui sarana daring.
Maka, rakyat tak punya yang juga pemilik sah dari bangunan dan negara ini kemudian bisa tetap mendapatkan kesempatan yang sama tanpa perlu membeda-bedakan status kemampuan ekonomi. Jadi kalau ke puncak rakyat pun bisa punya kesempatan asalkan bisa mendapatkan tiket yang setiap harinya dibatasi itu. Ini lebih adil!
Adanya cara pengaturan 'fasilitas publik' atas candi Borobudur mengingatkan pada cara pemerintah kota Istambul mengatur dan memberi fasilitas kepada warganya agar bisa menikmati makanan dan pemandangan dari selat Bhosporus yang indah. Di tepian selat itu ada lima restauran publik yang sangat enak dan punya tempat strategis. Turis asing bisa mendapatkan kesempatan di sana dengan harga selangit. Tapi, khusus untuk warga lokal mereka cukup hanya membayar sepertiganya. Sangat mahal bagi orang asing, murah bagi warga Turki sendiri!
Lalu dengan cara apa mengaturnya agar tak jadi rebutan? Maka dibuatlah aturan bagi siapa saja warga lokal yang ingin makan di restoran kelas satu itu harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapat nomor antrean. Di sini, kapasitas pengunjungpun secara otomatis dibatasi sekaligus diatur.
Akibatnya, jangan heran kalau lihat warga Istanmbul dari kalangan bukan 'the have' bisa membawa anak-anak dan keluarganya makan serta bercengkerama di restoran itu. Terakhir orang Indonesia yang bisa dilihat makanan di restoran elit itu adalah keluarga musisi top Ahmad Dhani. Padahal kalau di sana, bukan orang yang kaya seperti Dhani saja yang bisa menikmatinya, rakyat jelata pun bisa asalkan mendaftar dahulu atau pesan tempat duduk jauh-jauh hari sebelumnya.
Efek dari pengaturan ini membuat restoran-restoran elit itu laris manis. Apalagi pada saat bulan puasa.Tempat duduk di restoran itu sudah penuh dipesan tiga bulan sebelumnya untuk menggelar acara buka puasa. Dan ini juga menjadi ajang pendidikan kepada warga kota agar mau tertib dan antre. Orang lokal atau warga biasa tak bisa 'selonong boy' nongkrong di restoran itu. Pemerintah Turki pun tak segan memberikan subsidinya.
Cara pengaturan seperti itu bisa menjadi salah satu alternatif sehingga semua orang, tak hanya orang kaya saja', bisa menikmati puncak candi Borobudur. Tak usah malu belajar pada Turki yang sering dituduh sarang Islamis, kadrun, dan Wahabi.
Ingat pepatah China juga sudah mengajarkan satire: Ketika sebuah bangunan monumen berdiri, ke manakah para tukang batu? Atau nasihat dari cendikiawan Iran Ali Syariati: Monumen besar itu dibangun dengan darah rakyat jelata.
Sekali lagi, jangan lestarikan candi Borobudur sebagi monumen penindasan rakyat kecil...!


