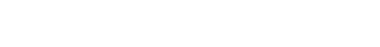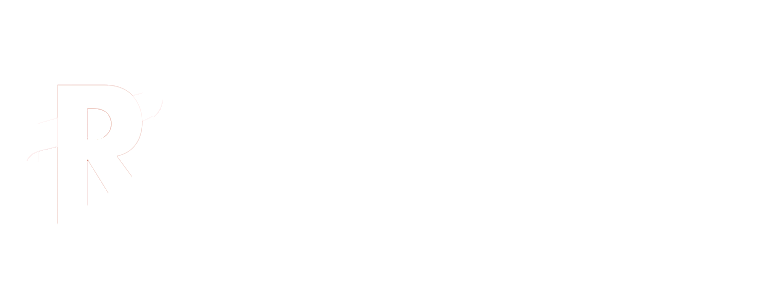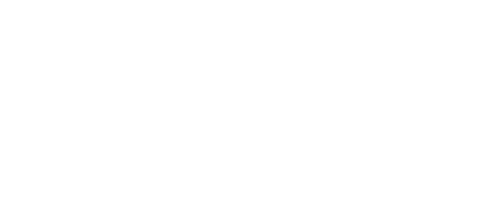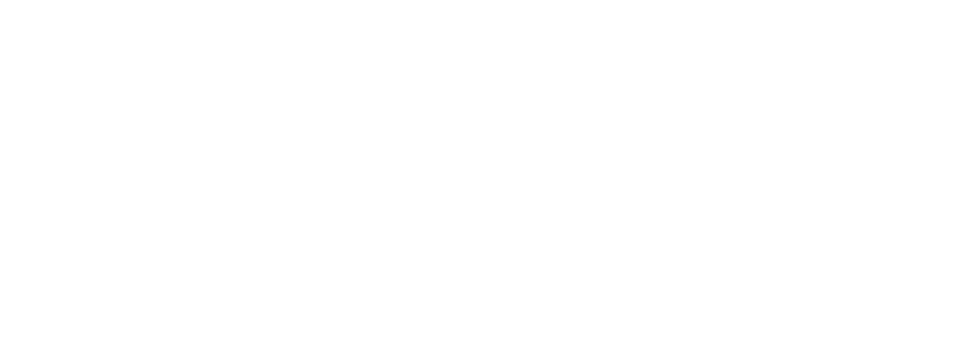Mitsaqan Ghalidza : Pernikahan, dan Perjanjian Agung
AgamaAda gambaran yang menarik untuk itu. Pasca PD II, terlihat kecenderungan bahwa pernikahan kandas setelah tujuh tahun kebersamaan. Sindrom ini disebut ‘ seven years itch of marriage’ dan berlangsung sampai sekitar era 80-an. Bahkan beredar juga ‘rumus universal’ yang menyatakan separuh pernikahan akan berakhir dengan perceraian. Asumsi yang mencemaskan, bukan?
Untungnya itu bukan konstanta. Cara membaca yang lebih tepat seharusnya begini: dari semua pernikahan yang karam, lebih dari separuhnya terjadi sebelum tahun ketujuh yang kelam. Kasus terbanyak? Pada tahun keempat yang penuh tengkar berdentam-dentam. Maka berkembanglah teori berikutnya tentang ‘ Why the fourth year is the hardest’. Pasokan cinta yang mulanya memadai--bahkan oversupply sebagai modal utama agar bisa happy sehidup semati--dalam kenyataannya menguap lebih cepat dari hilangnya embun pagi.
Romantisasi dan mitosisasi slogan ‘ and they live happily ever after’ sebagai pesan subliminal dongeng urban yang renyah dikunyah, seringkali berbalik menjadi ranjau tersembunyi yang bakal mencabik-cabik kebahagiaan pasangan yang menikah hanya berdasarkan hasrat badaniah. Daya pukau cinta lenyap paling lama setahun setelah bulan madu yang indah.
Perhatikan juga hasil survei ini. Pada dekade pertama milenium ketiga (2010) sebuah riset global di sepuluh kota (Doha, Cape Town, London, Tokyo, Mexico City, Sydney, New York City, Paris, Ottawa dan Roma) dilakukan majalah The Economist untuk mengetahui berapa lama pernikahan warga kosmopolitan bisa bertahan. Hasilnya: tak ada yang bisa mencapai dua dasawarsa! Masa pernikahan terlama 18 tahun (Roma, Italia) dan tersingkat 5,5 tahun (Doha, Qatar). Ini menambah deretan bukti betapa tak mudahnya menjaga komitmen Perjanjian Agung nan suci.
Jadi, ketika hari ini saya mensyukuri hari jadi pernikahan ke-24, artinya saya (dan istri) sudah melewati rerata tahun pernikahan global yang gawat. Alhamdulillah. Sejumlah jebakan, perangkap, dan ranjau kehidupan sepanjang perjalanan berhasil dilalui dengan aman--untuk sementara waktu sampai saat ini.
Kenapa sementara? Sebab gamblang juga di masyarakat, pasangan yang hidup harmonis sampai seperempat abad—bahkan lebih lama—tetiba ambyar porak-poranda akibat meleng sesaat. Ada yang menimpa pasangan artis-selebriti, ada yang terjadi pada keluarga pemuka agama-da’i. Perjanjian Agung terbanting menjadi serpihan berkeping-keping.
Hari ini—24 tahun silam—saya menikah. Alhamdulillah Itu berarti 288 purnama yang menyejarah. Allah mengaruniai kami tiga putri dengan genetika multibudaya: Minangkabau (50%), Sumba (25%), Tionghoa (12,5%) dan Sunda (12,5%). Repotnya, pada saat yang sama mereka juga tak bisa disebut “orang Minang”, “orang Sumba”, “orang Tionghoa” atau “orang Sunda”.
Ini akibat dalam paradigma Minang, identitas kesukuan ditakar melalui jalur matrilineal. Seorang anak yang lahir dari ibu non-Minang dilihat sebagai “bukan Minang”. Sebaliknya dalam paradigma Sumba, Tionghoa dan Sunda yang berbasis garis patrilineal, identitas anak ditimbang berdasarkan etnis sang ayah. Sehingga, anak-anak saya pun “bukan Sumba”, “bukan Tionghoa”, “bukan Sunda”.
Jadi mereka termasuk suku apa? Ya, sudahlah. Indonesia saja.
(”Gitu saja kok repot!” pesan Gus Dur sewot)